Opini
Arti Warna Kuning Makna Warna Kuning Kerajaan Melayu Kerajaan Nusantara Kesultanan Kutai Kartanegara Kesultanan Melayu Sejarah Warna Kuning
Warna Kuning Tradisi Nusantara Sakral dengan Batasan
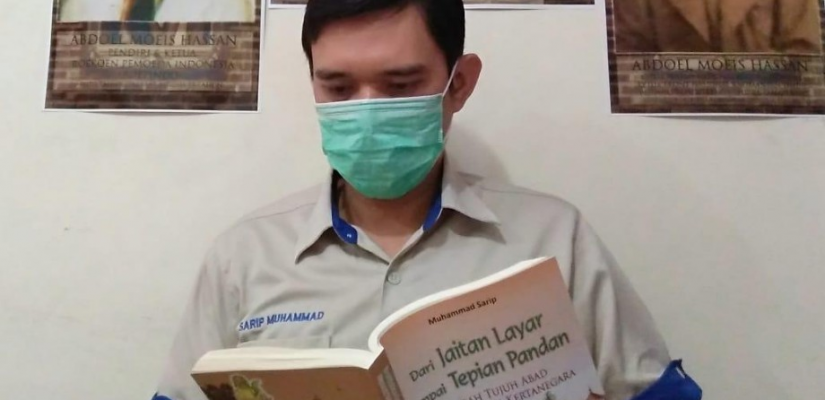
Penggunaan warna kuning untuk pakaian Kesultanan Melayu serupa dengan baju zirah alias kostum perang kesatria Hindu dalam mitologi India. Para kesatria dalam epos Mahabharata umumnya memakai baju zirah berwarna kuning keemasan.
Oleh: Muhammad Sarip, Penerima Sertifikat Kompetensi Bidang Sejarah dari Kemdikbud-BNSP
Warna kuning punya makna spesial dalam tradisi masyarakat Melayu. Selain berfungsi estetis, kuning juga termasuk warna sakral. Warna yang diadopsi dari simbol matahari dan warna emas ini melambangkan kejayaan, keagungan, kemegahan, serta kesucian. Begitu spesialnya warna kuning, penggunaannya terbatas pada benda dan sarana tertentu yang bernilai sakral.
Berita Terkait
Perhatian manusia terhadap estetika pewarnaan menunjukkan berkembangnya masyarakat yang berkebudayaan. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi (2013: 150–151), Koentjaraningrat mendeskripsikan bahwa kebudayaan mewujud dalam tiga bentuk. Kebudayaan bermula dari gagasan, ide, nilai, dan sebagainya yang bersifat abstrak. Lalu terbentuk sistem sosial yang yang sifatnya konkret. Kemudian terbentuklah benda-benda konkret hasil karya manusia.
Benda yang diberi warna kuning contohnya beras dalam ritual tabur beras kuning. Tradisi ini banyak dilakukan di Nusantara dalam sejumlah prosesi adat seperti pernikahan, upacara keselamatan, tepung tawar, pesta rakyat, dan sebagainya.
Contoh berikutnya yang mengistimewakan warna kuning adalah pakaian adat raja dan bangsawan kerajaan. Dalam tradisi Melayu, hanya kalangan elite istana yang boleh mengenakan pakaian berwarna kuning. Namun, kuning bukan warna tunggal kostum para sultan. Ada warna lain yang biasa dipakai seperti hitam dan putih.
Penggunaan warna kuning untuk pakaian Kesultanan Melayu serupa dengan baju zirah alias kostum perang kesatria Hindu dalam mitologi India. Para kesatria dalam epos Mahabharata umumnya memakai baju zirah berwarna kuning keemasan. Ini berbeda dengan baju zirah Eropa yang umumnya berwarna putih, silver atau gelap. Memang sebelum eksistensi Kesultanan Melayu, sejarah Nusantara dulunya merupakan masyarakat Hindu-Buddha yang terpengaruh India. Akan tetapi, lagi-lagi kuning bukan satu-satunya warna baju perang Hindu-India. Khusus para kesatria kubu Pandawa memakai baju zirah berwarna perak.
Lampin berwarna kuning juga digunakan sebagai popok bayi Aji Batara Agung Dewa Sakti, yang kelak mendirikan Kerajaan Kutai Kertanegara. Dihikayatkan, bayi Aji ini diturunkan dari kayangan dalam kondisi sudah berbebat lampin kuning. Simbolisasi ini tertulis dalam naskah klasik Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara beraksara Arab Melayu (1849: 3).
 Teks “lampin kuning” dalam manuskrip Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara, halaman ke-3. Sumber: Berkas digital di Perpustakaan Berlin, Jerman.
Teks “lampin kuning” dalam manuskrip Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara, halaman ke-3. Sumber: Berkas digital di Perpustakaan Berlin, Jerman.
Selain lampin kuning, historiografi tradisional Salasilah Kutai juga mencatat adanya kain kuning yang khusus digunakan untuk membungkus kepala orang mati dan kerbau dalam ritual adat klasik (1849: 13). Kain kuning juga digunakan sebagai kelambu atau pembungkus untuk makam yang dikeramatkan. Ritual penyematan kain kuning ini merupakan warisan budaya pra-Islam. Maknanya sebagai pengagungan terhadap ruh orang suci.
 Teks “kain kuning” dalam manuskrip Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara, halaman ke-13. Sumber: Berkas digital di Perpustakaan Berlin, Jerman.
Teks “kain kuning” dalam manuskrip Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara, halaman ke-13. Sumber: Berkas digital di Perpustakaan Berlin, Jerman.
Contoh lain lagi adalah rumah panggung khas Melayu. Secara umum hunian berkonstruksi kayu ini dindingnya dicat kuning. Namun, kuning bukan warna tunggal. Terdapat ornamen lain di rumah Melayu yang berwarna hijau, putih, merah, biru, dan hitam.
Pengecualian untuk keraton kesultanan bercorak Melayu yang berkonstruksi beton. Ada sebuah keraton yang arsitekturnya bergaya Eropa dan meninggalkan kekhasan Melayu. Seluruh bangunan dari sisi luar tampak dominan warna putih. Istana sultan tersebut sejak masa Orde Baru beralih fungsi sebagai museum.
Ketika pada awal abad ke-21 pemerintah daerah membangunkan kedaton yang baru, arsitekturnya mengacu wujud bangunan klasik versi kayu. Namun, konstruksinya dari beton. Warna dominan dinding luar adalah putih.
Sedemikian sakralnya kuning dalam tradisi Melayu-Nusantara, penggunaannya tidak digeneralisasi pada semua benda dan sarana publik. Jika semua ruang dan tempat diwarnai kuning, maka ia bukan lagi warna yang spesial. Bahkan bisa menjelma sebagai politik penyeragaman identitas yang mengabaikan kebinekaan. Elemen kuning sakral sesuai proporsinya.
Di Indonesia sendiri marak penghidupan kembali kesultanan dan kerajaan sejak awal era Reformasi. Ada yang difasilitasi oleh pemda, tetapi misinya tidak bermaksud membangkitkan kembali feodalisme dan sistem pemerintahan berdasarkan garis keturunan bangsawan. Kesultanan versi baru adalah pemangku serta pelestari adat dan budaya, bukan pemegang otoritas politik seperti sebelum 1960. Regulasi Negara Indonesia juga tidak memungkinkannya.
Pemerintah dan sultan/raja baru saling memahami ada domain yang berbeda antara otoritas birokrasi negara dan lembaga kesultanan modern dalam koridor NKRI. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap dijalankan oleh gubernur, bupati/wali kota, sedangkan kesultanan berfungsi sebagai simbol pelestari adat, seni, dan budaya.
Kedudukan sultan modern di Berau, Paser, Kutai, Banjar, dan di daerah lainnya di Indonesia masa kini, berbeda dengan konsep negara kerajaan parlementer. Misalnya di Malaysia dan Inggris, raja atau ratu statusnya kepala negara sehingga dilibatkan dalam urusan seremoni kenegaraan, seperti peresmian event, pelantikan pejabat, gunting pita, dan lain-lain. Adapun di Indonesia, para sultan dan raja yang bukan kepala daerah tidak terlibat dalam urusan seremoni pemda. Terlebih lagi urusan birokrasi dan kebijakan pemda. Ada pemisahan yang jelas antara ranah birokrasi negara dan lembaga adat masa kini.
Jika sultan atau pemangku adat ingin memiliki wewenang dalam bidang politik dan kebijakan lainnya, kedudukannya sebagai warga negara sama di mata hukum. Ada mekanisme pilkada yang boleh diikuti para tokoh adat atau sultan. Di Indonesia, Sultan Banjar Pangeran Khairul Saleh pernah menjadi peserta pilkada. Rakyat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, memenangkannya sehingga ia terpilih sebagai Bupati Banjar selama dua periode (2005–2015).
Dalam konteks warna kuning sebagai kekhasan adat, di sinilah institusi masyarakat adat berperan. Jika ada oknum warga atau kelompok tertentu yang mengusung label adat lalu misalnya menabur beras berwarna biru, maka ini bisa diduga terjadi pelanggaran adat. Begitu pula jika kelambu kuning di makam tokoh yang dihormati diganti dengan kelambu cokelat, maka ini juga patut diduga melanggar adat.
Adapun jika pemerintah membangun fasilitas publik semisal gedung instansi tertentu, maka urusan arsitektur, konstruksi, dan warnanya merupakan domain pemerintah. Ada batasan bagi lembaga adat untuk tidak mengintervensi urusan teknis yang bukan termasuk ranah adat, seni, dan budaya.
Tidak hanya fasilitas publik yang dibangun pemerintah. Terhadap bangunan milik swasta pun, itu adalah hak setiap individu atau komunitas untuk merancang arsitektur termasuk warnanya. Tentu saja, perizinan diurus kepada instansi yang berwenang. Pemerintah tidak berhak memaksa warganya untuk mengecat rumah misalnya dengan warna merah-putih, meskipun maknanya bagus sebagai simbol bendera kebangsaan Indonesia. Terkecuali rumah warga itu dibangun dengan biaya dari APBD.
Adat istiadat sebagai kebudayaan karya cipta, rasa, dan karsa manusia semestinya bersinergi dengan kemajuan peradaban. Nilai-nilai kearifan lokal, sebagaimana juga dalil agama, tidak selayaknya diperalat untuk kepentingan politik identitas yang merugikan peradaban dan kemaslahatan publik.











